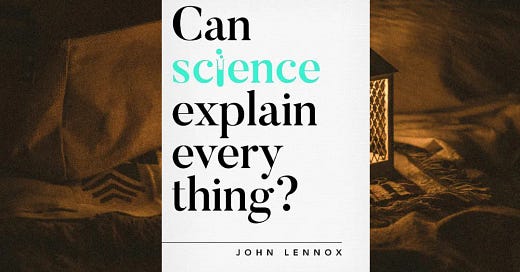Can Science Explain Every Thing #3: Hanya Sains Sumber Pengetahuan?
Di serial tulisan sebelumnya, kita membahas bagaimana Prof. Lennox memaparkan bahwa menjadi saintis tidak serta-merta menuntut kita melepas keimanan kita dan bagaimana sains, melalui methodolocial naturalism, tidak lah bertentangan dengan keimanan (ataupun ketiadaan iman) seseorang. Kita juga melihat bagaimana para ilmuwan abad pertengahan justru didominasi oleh orang-orang yang beriman seperti Galileo dan Newton.
Selanjutnya, pertanyaan yang mungkin muncul: meskipun kebanyakan ilmuwan abad pertengahan beriman, bukankah kebanyakan ilmuwan modern seperti Hawking, Sagan, Dawkins tidaklah beriman? Tidakkah ini mengindikasikan bahwa perkembangan sains modern berpengaruh terhadap kepercayaan ilmuwan pada Tuhan? Dan kalau para ilmuwan yang menjadi garda depan ilmu pengetahuan saja bisa sampai pada kesimpulan pada ketiadaan Tuhan, tidakkah pandangan mereka ini layak dipercaya?
Merespons pertanyaan-pertanyaan di atas memerlukan kita untuk mundur selangkah dan melihat beberapa asumsi tersembunyi di balik pertanyaan-pertanyaan di atas. Yang pertama adalah asumsi bahwa setiap pernyataan yang muncul dari seorang saintis dianggap sebagai sains itu sendiri. Ini adalah asumsi yang keliru. Ketika Carl Sagan berkata misalnya bahwa “alam semesta adalah segala sesuatu yang pernah ada, sedang ada, dan akan ada”, ia sebetulnya tidak sedang mengeluarkan pernyataan saintifik yang dihasilkan melalui metode saintifik. Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan “gravitasi mengikuti hukum kuadrat berkebalikan (inverse-square law)” misalnya. Pernyataan kedua ini merupakan sebuah teori sains yang telah teruji melalui observasi dan eksperimen serta memiliki kemampuan prediksi yang akurat (dalam batas-batas fisika klasik Newtonian). Teori gravitasi ataupun teori sains lainnya in itself tidaklah mengindikasikan bahwa hanya alam semesta dan penyebab natural nya saja yang ada. Ingat, sains bekerja dengan asumsi methodological naturalism (bahwa selalu ada penyebab natural), bukan membuktikan philosophical naturalism (bahwa hanya ada penyebab natural).
Di sini lah pentingnya memilah mana teori sains yang diajukan seorang saintis dan mana posisi filosofisnya. Membedakan antara keduanya membuat kita bisa saja menerima teori saintifiknya tanpa mengakui posisi filosofis yang dianut ilmuwan tersebut. Maka, menolak pernyataan non-saintifik seorang saintis tidak sama dengan menolak sains itu sendiri. Dengan kata lain, pandangan saintis tentang keberadaan (ataupun ketidakberadaan) Tuhan adalah posisi filosofis yang terpisah dari kontribusi saintifiknya. Poin ini bahkan sudah jauh lebih dulu ditekankan oleh Al-Ghazali dalam pembuka karyanya, Tahafut al-Falasifah, bahwa keakuratan ilmu matematika yang dipegang para filsuf Muslim tidak berkaitan dengan kebenaran posisi filosofis mereka tentang Tuhan.
Asumsi kedua di balik pertanyaan-pertanyaan tadi adalah keyakinan bahwa sains lah satu-satunya sumber pengetahuan yang valid, yang biasa dikenal sebagai saintisme. Maka, ketika saintis yang sudah berjibaku dengan metode saintifik “tidak menemukan Tuhan” dalam sains, Tuhan pun dianggap tidak ada. Tentu saja ini asumsi yang tidak tepat. Sebagaimana sempat disinggung di tulisan sebelumnya, sains menjelaskan relasi antara besaran-besaran natural di alam. Melalui methodological naturalism, sains memang membatasi diri dengan penjelasan natural. Ia tak bisa mengklaim apa pun di luar itu. Lebih dari itu, pengetahuan rasional tidak dibatasi oleh sains saja. Pengetahuan seperti hukum dasar logika, misalnya, tidak butuh sains untuk dibuktikan kebenarannya.
Prof. Lennox lalu memberi ilustrasi menarik untuk menjelaskan kekeliruan di atas. Bayangkan Bibi Maltida sedang membuat kue. Seorang saintis bisa menjelaskan komposisi kue tersebut, apa proses kimia dan fisika yang terjadi, bahkan mungkin hingga membuat model matematis pembuatan kue tersebut. Tapi, para saintis ini tidak bisa menjawab mengapa kue dibuat hanya dari sains saja! Satu-satunya cara mengetahui mengapa kue tersebut dibuat adalah melalui testimoni dari si pembuat kue sendiri!
Maka, tidaklah tepat ketika kepercayaan pada Tuhan dianggap sebagai delusi. Delusi terjadi ketika suatu kepercayaan tetap dianggap benar bahkan dengan adanya bukti-bukti meyakinkan yang menyanggah kepercayaan tersebut. Tapi, seperti kita lihat, sains, bahkan dengan segala perkembangan pesatnya di era modern ini, tidak bisa membuktikan ketiadaan Tuhan. Di sisi lain, sains juga tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Tetapi, ini bukan berarti Tuhan tidak ada, karena sains bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan.
Sebagai penutup tulisan ini, saya ingin menyadur respons Prof. Lennox saat mendengar pernyataan bahwa “kepercayaan pada surga dan hidup sesudah kematian hanya seperti fantasi bagi mereka yang takut kegelapan”. Jawab beliau: “ketidakpercayaan pada Tuhan hanyalah fantasi bagi mereka yang takut pada cahaya.”
Catatan: Bagi yang tertarik pada penjelasan lebih dalam tentang sumber-sumber pengetahuan, tentang mengapa rasional tidak sama dengan saintifik, dan tentang bagaimana memposisikan sains dan logika dalam memahami konsep seperti Tuhan dan mu'jizat, silahkan bisa membaca lebih jauh di buku “Logika Keimanan”.