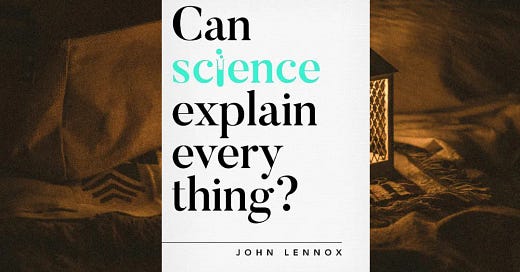Can Science Explain Every Thing #2: Menjadi Saintis Harus Melepas Iman?
Prof. Lennox membuka buku “Can Science Explain Every Thing?” dengan cerita pengalaman pribadi beliau semasa muda saat diperingatkan salah satu saintis senior. “Kalau mau berkarir di bidang sains, kamu harus meninggalkan keimananmu.” Begitu kurang lebih klaim yang disampaikan sang senior. Di era ketika banyak saintis tidak ragu mendemonstrasikan ketidakpercayaannya pada Tuhan, pandangan semacam itu mungkin mulai dianggap valid kebenarannya. Bahkan, tidak sedikit yang mengadopsi kepercayaan banyak ilmuwan soal Tuhan semata-mata karena mereka ilmuwan ternama. “Para ilmuwan yang kecerdasannya tak diragukan lagi saja sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan tidak ada. Sudah pasti ini kesimpulan yang valid, kan?”
Prof. Lennox mengkritisi klaim di atas dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah aspek empiris: jika meninggalkan keimanan menjadi syarat kesuksesan seorang ilmuwan, mestinya tidak ada orang beriman yang sukses menjadi saintis. Tapi, justru banyak peraih Nobel yang percaya keberadaan Tuhan, sebagaimana banyak juga peraih Nobel yang tidak percaya adanya Tuhan. Contoh yang cukup ekstrim adalah Nobel Fisika 1979 ketika Abdus Salam yang seorang Muslim dan Steven Weinberg yang seorang ateis bersama-sama mendapat Nobel (beserta Sheldon Glashow) atas kontribusi mereka mengintegrasikan elektromagnetik dan gaya lemah.
Aspek kedua, untuk melihat apakah betul saintis mesti menanggalkan keimanannya, kita perlu melihat bagaimana sains bekerja. Sebagaimana pernah saya singgung, sains bekerja dengan asumsi methodological naturalism. Artinya, sains selalu mengasumsikan adanya penjelasan natural di balik peristiwa-peristiwa di alam semesta. Adanya percepatan pada suatu benda pasti dibersamai adanya penyebab natural tertentu, dalam hal ini gaya. Keberagaman spesies pasti diakibatkan penyebab natural tertentu, dalam hal ini mutasi acak dan seleksi alam. Melihat konsep ini, kita bisa melihat bagaimana sains in itself tidak lah bertentangan dengan ateisme ataupun teisme. Sains mendeskripsikan bagaimana relasi antar besaran-besaran natural di alam. Ia tidak bicara soal sesuatu yang bersifat supernatural karena memang membatasi dirinya pada objek natural melalui methodological naturalism.
Lalu, apa yang bertentangan dengan keimanan pada Tuhan? Yang bertentangan bukanlah sains ataupun methodological naturalism, tapi philosophical naturalism. Ini adalah worldview atau pandangan yang percaya bahwa alam adalah segala sesuatu yang ada. Artinya, klaimnya selangkah lebih dalam daripada methodological naturalism: bukan sekedar mengasumsikan selalu adanya penyebab natural, pandangan ini mengklaim bahwa penyebab natural adalah satu-satunya penjelasan di balik fenomena alam. Tuhan, sebagai Dzat yang dipercaya bukan bagian dari alam, otomatis keberadaannya ditolak oleh pandangan ini.
Memahami perbedaan antara methodological naturalism dan philosophical naturalism membantu menjelaskan mengapa banyak sekali ilmuwan sejak abad pertengahan adalah penganut kepercayaan pada Tuhan. Para saintis ini tetap bisa memproduksi pengetahuan saintifik tanpa harus menanggalkan keimanan mereka karena memang metode saintifik tidaklah bertentangan dengan kepercayaan saintis tersebut tentang Tuhan, terlepas dia percaya keberadaan Tuhan atau tidak. Bahkan, banyak dari saintis abad pertengahan seperti Isaac Newton yang melihat keteraturan alam sebagai manifestasi kekuasaan Tuhan.
Lalu, bagaimana dengan Galileo? Bukankah konflik antara Galileo dan gereja jelas menunjukkan ketegangan antara agama dan sains? Yang sebetulnya terjadi adalah pertentangan antara teori sains yang diusung Galileo dengan teori filsafat alam Aristoteles yang saat itu dipegang kalangan gereja dan digunakan untuk menjustifikasi klaim wahyu yang seperti mengindikasikan Bumi sebagai pusat alam semesta. Galileo termasuk yang mengajukan teori bahwa Bumi justru mengeliling matahari, yang dipostulasikan Copernicus. Galileo tidak sedang mengkritik agama secara umum, apalagi keberadaan Tuhan. Bahkan, sebagaimana dikutip Prof. Lennox, Galileo berpandangan bahwa “Hukum Alam ditulis oleh Tangan Tuhan melalui bahasa matematika,” bukti bahwa ia tidak melihat pertentangan antara teori sainsnya dan keimanannya. Kritik terhadap tradisi Aristoteles ini bahkan sebetulnya sudah dilakukan banyak ilmuwan Muslim jauh sebelum Galileo lewat tradisi kitab-kitab Syukuk (Keraguan), seperti Syukuk ‘ala Batalamyus (Keraguan atas Ptolomeus) karya Ibn al-Haytham yang mengkritisi model geosentris Ptolomeus. Tradisi kritik ini yang bahkan menurut George Saliba membuka jalan bagi revolusi saintifik di era Copernicus sehingga bisa menggantikan filsafat alam Yunani dengan sains modern yang kita kenal saat ini.
Kesimpulan sementara yang bisa kita dapat dari tulisan ini: memilih antara menjadi saintis atau seseorang yang beriman adalah dikotomi palsu karena metode saintifik sebagai enterprise pengetahuan tidaklah bertentangan dengan kepercayaan saintis tersebut terkait agama dan Tuhan. Di tulisan selanjutnya, kita akan masuk lebih jauh membahas pandangan Prof. Lennox tentang sains sebagai sumber pengetahuan.